Opini
Tinjauan Kriminologis Terhadap Fenomena Tewas tak Wajar di Maluku Utara
Teori-teori kriminologi kontemporer telah bergeser dari pendekatan klasik yang berfokus pada pelaku kejahatan sebagai individu rasional
Rahmat Hi Abdullah
Akademisi Fakultas Syariah IAIN Ternate
MENCERMATI informasi tentang peristiwa bunuh diri atau tewas tak wajar di Maluku Utara yang belakangan ini mengemuka baik melalui media pemberitaan maupun media sosial, satu hal yang harus disadari bersama bahwa masalah sosial tersebut memerlukan pendekatan multidimensional dalam pemahaman dan penanganannya.
Sebagai akademisi ilmu hukum, saya memandang perlu untuk mengkaji fenomena ini dari perspektif kriminologi modern yang tidak lagi terbatas pada paradigma legalistik semata, melainkan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan psikologis yang melatarbelakanginya.
Teori-teori kriminologi kontemporer telah bergeser dari pendekatan klasik yang berfokus pada pelaku kejahatan sebagai individu rasional, menuju pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang konteks sosial dan struktural.
Terhadap peristiwa demi peristiwa bunuh diri atau tewas tak wajar di Maluku Utara, teori Anomie yang dikembangkan Robert K. Merton (1938) rasanya relevan dijadikan pendekatan untuk 'membedah' fenomena dimaksud sekalipun perlu diperluas.
Merton menjelaskan bahwa ketidakselarasan antara tujuan budaya (cultural goals) dengan sarana institusional (institutional means) dapat mendorong perilaku menyimpang, termasuk bunuh diri.
Di Maluku Utara, dapat disebutkan bahwa kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan mental, dan perubahan struktur sosial menciptakan kondisi anomik yang menekan individu.
Teori Anomie yang dikembangkan oleh Merton menawarkan kerangka analisis struktural untuk memahami perilaku menyimpang, termasuk bunuh diri atau tewas tak wajar.
Berbeda dengan konsep Anomie Durkheim yang berfokus pada absensi norma, Merton mengembangkan konsep yang lebih spesifik tentang ketegangan struktural (structural strain) yang muncul akibat kesenjangan antara tujuan budaya dan sarana institusional sebagaimana telah disebutkan sebelumnya untuk mencapai tujuan tersebut.
Secara konkrit, jika teori Merton digunakan sebagai pendekatan dalam mengurai fenomena bunuh diri yang belakangan terjadi di Maluku Utara maka setidaknya dapat diuraikan sebagai berikut:
Ketegangan Struktural di Maluku Utara
Ketegangan struktural di Maluku Utara, dapat disebutkan termanifestasi dalam beberapa bentuk di antaranya pertama, Kesenjangan Ekonomi: bahwa penetrasi ekonomi pasar ke dalam masyarakat tradisional menciptakan aspirasi konsumtif dan definisi kesuksesan material, namun infrastruktur ekonomi yang belum berkembang dan distribusi sumber daya yang tidak merata membatasi akses sebagian besar masyarakat terhadap kesempatan ekonomi.
Dalam Bahasa sederhananya, terhadap masyarakat Maluku Utara sebagai objek pasar yang mengalami perkembangan meningkat seiring status sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, secara bersamaan tidak diimbangi dengan modal publik misalnya pembangunan infrastruktur berkualitas yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, beberapa diantaranya adalah akses layanan dasar dan konektivitas antar wilayah. Akhirnya kesenjangan dimaksud berdampak pada kondisi masyarakat yang seakan membenarkan bahwa 'yang kaya semakin kaya, dan yang miskin terima nasibnya'.
Kedua, Transformasi Sosial: Perubahan cepat dari struktur masyarakat tradisional ke modern menghasilkan pergeseran sistem nilai dan ekspektasi sosial.
Masyarakat Maluku Utara dihadapkan pada definisi keberhasilan "modern" (pendidikan tinggi, pekerjaan formal, gaya hidup urban), namun akses terhadap sarana untuk mencapai tujuan tersebut sangat terbatas.
Dalam konteks Maluku Utara, transformasi sosial ini terjadi pada individu maupun sistem sosial. Ketiga, Disrupsi Sistem Sosial: Dalam perspektif sosiologis, disrupsi ini merupakan fase dimana terjadinya sistem perubahan sosial secara lebih radikal.
Jadi benar-benar tercabut dari akarnya (KBBI). Banyak sistem atau tata sosial lama yang tergantikan dengan sistem baru.
Relasi-relasi sosial budaya mengalami perubahan mulai dari bentuk, media, bahkan waktu dan Bahasa. Perubahan besar-besaran ini terjadi akibat inovasi dan teknologi, sehingga mengubah cara hidup manusia.
Namun, dapat dipastikan bahwa faktor kunci dari semua proses, fase, dan tahapan perubahan-perubahan tetap tunggal yakni manusia.
Itulah kenapa, munurut penulis dukungan tradisional dan institusi sosial harus benar-benar dijaga serta ditumbuhkan bersama demi menghindari hal-hal yang disebut krisis personal. Bagaimana dengan kondisi ini di Maluku Utara serta cara adaptasinya?
Lima Moda Adaptasi Merton dalam Konteks Maluku Utara
Merton mengidentifikasi lima cara individu beradaptasi terhadap ketegangan struktural, yang jika diamati dalam konteks bunuh diri di Maluku Utara dapat diuraikan sebagai berikut:
Pertama, Konformitas (conformity). Yaitu individu menerima baik tujuan budaya maupun sarana institusional. Di Maluku Utara, kelompok ini adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial-ekonomi, misalnya melalui pendidikan atau migrasi yang berhasil. Kelompok ini cenderung memiliki risiko bunuh diri rendah karena relatif berhasil mengintegrasikan aspirasi dan kesempatan.
Kedua, Inovasi (innovation). Yaitu individu menerima tujuan budaya tetapi menolak atau tidak memiliki akses terhadap sarana institusional yang sah, sehingga mengembangkan cara-cara alternatif (sering kali ilegal).
Di Maluku Utara, hal ini terlihat pada terjadinya aktivitas-aktivitas ilegal seperti Online Prostitution dengan memanfaatkan perkembangan teknologi atau aktivitas ekonomi informal lainnya.
Ketika jalur inovasi ini gagal atau menghadapi sanksi sosial/hukum yang berat, individu dapat mengalami krisis identitas yang memicu ide bunuh diri.
Ketiga, Ritualisme (ritualism). Yakni individu menurunkan aspirasi atau menolak tujuan budaya dominan sambil tetap mematuhi sarana institusional.
Di Maluku Utara, ini tercermin pada individu yang "pasrah" dengan kondisi kemiskinan namun tetap mengikuti aturan sosial.
Meskipun jarang terkait langsung dengan bunuh diri, ritualisme jangka panjang dapat menghasilkan kondisi alienasi dan kehilangan makna hidup yang meningkatkan risiko depresi kronis.
Keempat, Retreatisme (Retreatism). Berupa individu yang menolak baik tujuan budaya maupun sarana institusional yang sah.
Di Maluku Utara, retreatisme termanifestasi dalam perbuatan-perbuatan atau kasus penyalahgunaan narkoba, alkoholisme, atau penarikan diri dari interaksi sosial.
Kondisi retreatisme berkepanjangan berkorelasi kuat dengan risiko bunuh diri karena individu mengalami isolasi sosial dan kehilangan struktur makna.
Kelima, Pemberontakan (Rebellion). Yaitu individu menolak tujuan budaya dan sarana institusional yang ada, dan berusaha menggantikannya dengan sistem nilai alternatif.
Dalam konteks Maluku Utara, kondisi pemberontakan ini dapat diakitkan dengan bunuh diri yang belakangan terjadi, khususnya ketika upaya pemberontakan gagal atau ketika individu menggunakan bunuh diri sebagai bentuk protes atau pernyataan sikap.
Kesimpulan
Teori Anomie Merton, dengan berbagai derivasinya, memberikan kerangka komprehensif untuk memahami fenomena bunuh diri di Maluku Utara sebagai manifestasi dari ketegangan struktural yang muncul dalam masyarakat transisional.
Pendekatan ini menuntun kita untuk melihat bunuh diri bukan sekadar sebagai masalah individu atau kesehatan mental semata, melainkan sebagai gejala dari ketidakselarasan struktural yang memerlukan intervensi sistemik dan berbasis budaya.
Sebagai sikap akademis, penulis berpendapat bahwa fenomena bunuh diri di Maluku Utara memerlukan respons kebijakan yang integratif dengan mempertimbangkan dimensi hukum, kesehatan masyarakat, dan pembangunan sosial.
Pertama, diperlukan dekriminalisasi percobaan bunuh diri dan reorientasi kebijakan pidana menuju model kesehatan masyarakat.
Kedua, penguatan sistem deteksi dini dan intervensi krisis melalui pelayanan kesehatan mental berbasis komunitas.
Ketiga, pembangunan kapasitas lokal dalam penanganan trauma dan resiliensi komunitas.
Sekali lagi, paradigma kriminologi kontemporer mengajarkan kepada kita bahwa fenomena bunuh diri bukanlah semata kegagalan individual, melainkan cerminan dari kompleksitas interaksi antara individu dan struktur sosialnya.
Oleh karena itu, pendekatan hukum semata tidak cukup tanpa disertai kebijakan yang memulihkan keseimbangan sosial dan memperkuat ketahanan komunitas di Maluku Utara. (*)

















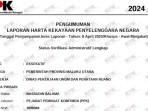



Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.